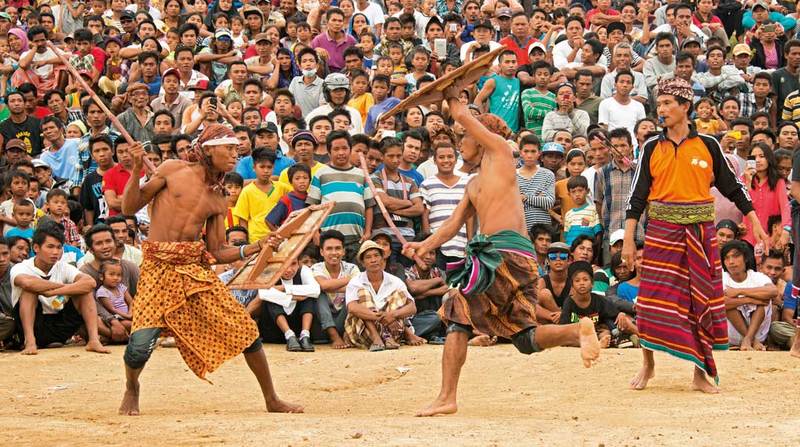Nusantara – Kain sasirangan merupakan warisan budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan yang hingga kini tetap lestari. Tak hanya indah secara visual, kain ini juga dipercaya memiliki kekuatan magis dan digunakan dalam berbagai upacara adat serta pengobatan tradisional.
Kampung Sasirangan, Sentra Produksi dan Wisata Budaya
Sentra pembuatan kain sasirangan berada di Kampung Sasirangan, yang terletak di Jalan Seberang Masjid, Kota Banjarmasin. Kampung ini dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai destinasi wisata budaya sekaligus pusat produksi kain khas Banjar tersebut.
Di tempat ini, wisatawan bisa menyaksikan langsung proses pembuatan kain sasirangan, dari tahap pewarnaan hingga hasil akhir, sekaligus membeli kain sebagai oleh-oleh khas Banjarmasin.
Asal Usul: Dari Kain Langgundi ke Sasirangan
Menurut catatan dalam Hikayat Banjar, kain sasirangan sudah dikenal sejak abad ke-7 dengan nama awal kain langgundi. Kisah legendarisnya melibatkan tokoh Patih Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa.
Dalam pencarian spiritual selama 40 hari 40 malam di atas rakit, Patih Lambung mendengar suara dari segumpal buih yang ternyata adalah Putri Junjung Buih. Sang putri bersedia menampakkan diri hanya jika permintaannya dipenuhi—yakni sebuah istana megah yang dibangun oleh 40 pemuda dan selembar kain panjang hasil karya 40 gadis, semuanya dalam satu hari.
Permintaan itu berhasil dipenuhi. Putri Junjung Buih pun muncul dengan mengenakan kain langgundi berwarna kuning, dan kemudian menjadi ratu Kerajaan Dipa. Dari sinilah kain langgundi berkembang dan kini dikenal sebagai kain sasirangan.
Kekuatan Magis dalam Kain Sasirangan
Lebih dari sekadar pakaian, masyarakat Banjar meyakini bahwa kain sasirangan memiliki kekuatan magis yang digunakan untuk pengobatan tradisional (batatamba) dan perlindungan dari roh jahat.
Kain yang dibuat berdasarkan pesanan khusus ini disebut kain pamintaan. Pembuatannya harus melalui serangkaian syarat dan ritual, termasuk selamatan. Warna kain juga disesuaikan dengan tujuan pengobatannya:
- Kuning: menyembuhkan penyakit kuning
- Merah: untuk sakit kepala atau insomnia
- Hijau: untuk lumpuh atau stroke
- Hitam: mengatasi demam dan gatal-gatal
- Ungu: meredakan sakit perut
- Cokelat: untuk gangguan kejiwaan
Kain sasirangan bukan hanya identitas budaya, tetapi juga simbol spiritual dan kearifan lokal masyarakat Banjar yang telah bertahan selama berabad-abad.
Kain Sasirangan: Dari Sarana Pengobatan hingga Busana Sehari-hari

Selain warna dan proses pembuatannya yang sarat makna, cara dan bentuk pemakaian kain sasirangan juga memiliki ketentuan tersendiri, terutama ketika digunakan sebagai kain pamintaan untuk pengobatan tradisional masyarakat Banjar.
Setiap bentuk pemakaian memiliki fungsi penyembuhan yang spesifik. Untuk mengobati demam atau penyakit kulit seperti gatal-gatal, kain dikenakan sebagai sarung (tapih bumin). Sementara itu, untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti diare, kolera, atau disentri, kain digunakan sebagai kemben (udat) yang membalut tubuh bagian atas.
Jika digunakan untuk mengurangi migrain, kain ini dipakai sebagai kerudung (kakamban), dililitkan atau disampirkan di kepala. Adapun untuk penyakit kepala seperti pusing atau nyeri berdenyut, pemakaiannya adalah sebagai ikat kepala (laung).
Dari Sakral ke Fungsional
Seiring waktu, kain sasirangan mulai mengalami pergeseran fungsi dan makna. Jika dulunya kain ini digunakan dalam konteks ritual dan pengobatan, kini ia juga dikenakan sebagai pakaian adat dalam acara resmi atau budaya.
Namun, arus globalisasi dan perkembangan tren mode perlahan mengikis nilai sakral kain sasirangan. Penggunaannya semakin meluas dan menjadi bagian dari busana sehari-hari. Bahkan, kain ini kini diolah menjadi berbagai produk seperti gorden, taplak meja, seprai, hingga sapu tangan.
Fenomena ini mencerminkan desakralisasi kain sasirangan, di mana unsur spiritual dan adat istiadat yang melekat pada kain mulai bergeser ke arah fungsional dan estetika modern.
Warisan Budaya Banjar yang Terus Berkembang
Nama sasirangan berasal dari metode pembuatannya, yaitu “sa” yang berarti satu dan “sirang” yang berarti jelujur. Kain ini dibuat melalui teknik tusuk jelujur yang kemudian diikat menggunakan benang atau tali, lalu dicelupkan ke dalam pewarna untuk menciptakan pola khas. Proses inilah yang menjadi ciri utama kain sasirangan.
Meski kerap disebut sebagai batik Banjar, kain sasirangan memiliki perbedaan mendasar dengan batik. Jika batik dibuat dengan cara mencanting malam (lilin) di atas kain, maka sasirangan lebih menonjolkan teknik ikat celup sebagai identitasnya.
Dari Serat Alam ke Serat Modern
Pada awalnya, sasirangan dibuat dari benang kapas atau serat kulit kayu. Namun seiring perkembangan teknologi, para perajin kini menggunakan berbagai jenis kain modern, seperti sutera, satin, santung, balacu, kaci, polyester, hingga rayon.
Perubahan juga terjadi dalam hal pewarnaan. Dulu, pewarna yang digunakan bersumber dari alam, seperti:
- Kunyit atau temulawak untuk warna kuning
- Buah mengkudu, gambir, atau kesumba untuk merah
- Kabuau atau uar untuk hijau
- Biji gandari untuk ungu
- Kulit buah rambutan untuk cokelat
Kini, banyak pengrajin beralih ke pewarna sintetis karena dianggap lebih praktis dan mudah didapat.
Motif dan Popularitas yang Terus Tumbuh
Kain sasirangan hadir dalam beragam motif, mulai dari sarigading, ombak sinapur karang, hiris pudak, bayam raja, hingga kambang kacang. Kreativitas para perajin juga terus melahirkan motif-motif baru yang memperkaya khazanah kain tradisional Banjar ini.
Kepopuleran kain sasirangan terus meningkat, terutama setelah ditetapkan sebagai seragam wajib bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pelajar di Kalimantan Selatan. Kini, kain ini tidak hanya hadir dalam upacara adat atau pengobatan tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari mode sehari-hari dan tersedia luas di berbagai toko oleh-oleh.