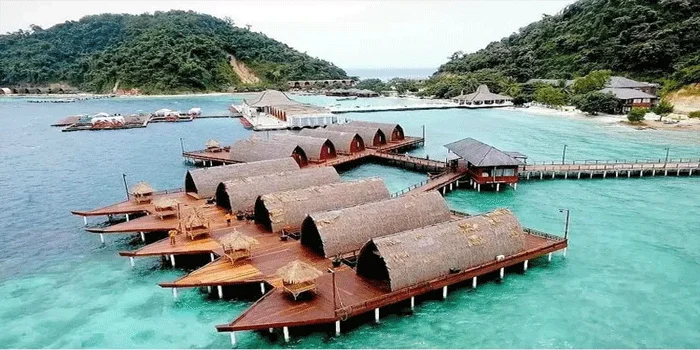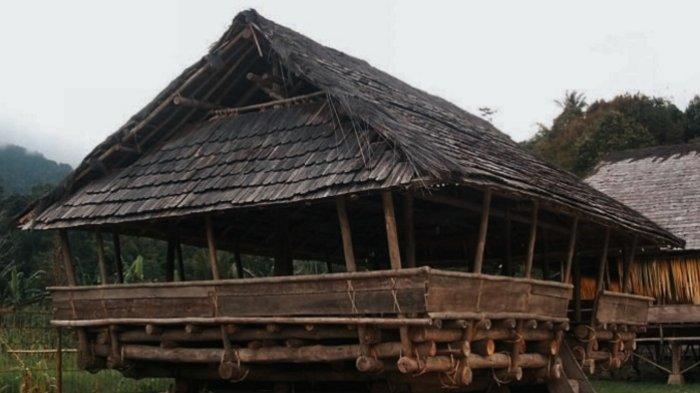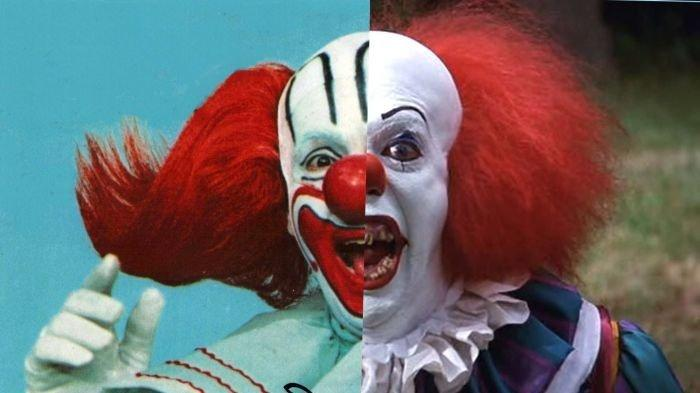Nusantara – Aroma seduhan kopi khas Pegunungan Muria tak hanya menggoda di dalam cangkir, tetapi juga menjadi denyut nadi kehidupan warga Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah.
Keharuman bunga kopi yang ranum bukan sekadar tanda biji bernilai jual tinggi. Bagi warga setempat, proses budidaya, panen, hingga pengolahan kopi telah menjadi tradisi kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, yang mereka sebut Wiwit Kopi.
Tahun ini, bertepatan dengan bulan kemerdekaan Agustus, tradisi Wiwit Kopi kembali digelar setelah vakum selama 15 tahun. Pesta rakyat tersebut berlangsung di Bukit Guyangan, Desa Japan, melibatkan para petani kopi dan seluruh warga.
Rangkaian acara dimulai dengan kirab gunungan berisi hasil bumi Pegunungan Muria—alpukat, mangga, jeruk pamelo, sayuran, hingga umbi-umbian. Yang istimewa, terdapat pula buah parijoto, tanaman khas yang hanya tumbuh di kawasan ini.
Selain sesaji gunungan, ditampilkan tarian Wiwit Kopi dan prosesi ngruwok atau memetik kopi langsung dari pohonnya. Acara ini menjadi penanda dimulainya musim panen raya kopi, yang biasanya berlangsung dari Juli hingga September.
Ketua Desa Wisata Japan, Mutohar, menjelaskan bahwa Wiwit Kopi adalah ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus sarana mempererat kebersamaan warga.
“Ini bukan sekadar ritual panen, tetapi simbol budaya yang kami lestarikan agar nilai-nilai lokal tetap hidup,” ujar Mutohar, Senin (11/8/2025).
Kemeriahan acara semakin terasa dengan hadirnya Bupati Kudus Samani Intakoris dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah. Mereka membaur bersama warga, menikmati suasana penuh keakraban. Bupati Kudus bahkan dipercaya mengawali prosesi ngruwok kopi, setelah doa bersama dan rebutan gunungan hasil bumi.
Negeri Kopi di Pegunungan Muria

Tradisi kearifan lokal warga Desa Japan yang sarat nilai budaya dan religius warisan Sunan Muria, menginspirasi Sam’ani untuk menetapkannya sebagai ikon budaya sekaligus destinasi wisata unggulan di Kota Kretek Kudus.
Menurut Sam’ani, potensi kopi di Desa Japan, Rahtawu, dan Colo di kawasan Pegunungan Muria sangat melimpah. Tradisi pengolahan kopi ini dinilainya mampu menjadi ciri khas Kudus yang dikenal luas. Ia pun menggagas rebranding kopi Muria menjadi “Kopi Kudus”, dengan harapan kopi robusta khas Muria memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar luar daerah.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, Mutrikah, turut menilai tradisi wiwit kopi sebagai magnet wisata yang dapat menggerakkan perekonomian desa-desa di kaki Pegunungan Muria. Menurutnya, kegiatan ini mampu memotivasi petani dan pelaku UMKM kopi untuk lebih menggali potensi kopi Muria, sehingga mendapatkan nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Kemeriahan wiwit kopi tahun ini menjadi wujud syukur para petani Desa Japan atas panen yang melimpah, sekaligus mempertegas identitas daerah tersebut sebagai “Negeri Kopi” di lereng Pegunungan Muria.