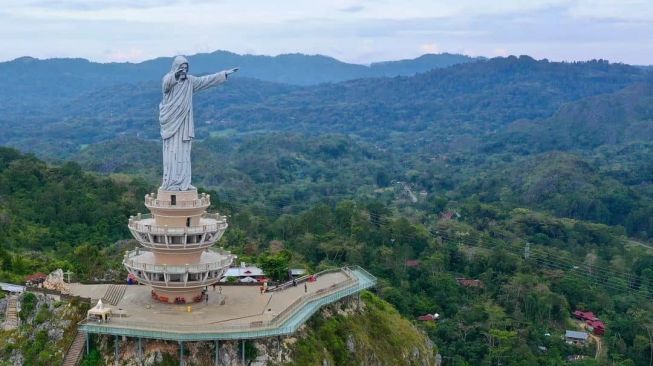Nusantara – Tradisi pemakaman adat Rambu Solo’ merupakan salah satu warisan budaya agung Tana Toraja yang telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun mancanegara. Namun di balik kemegahan upacara adat yang biasa terlihat, ada sebuah dusun terpencil yang justru memperlihatkan wajah berbeda dari tradisi ini—penuh kesetaraan, kesederhanaan, dan makna filosofis yang mendalam.
Dusun itu bernama Pangorean, terletak di Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Masyarakat menyebutnya dengan sebutan yang khas dan sarat nilai: Kampung Merdeka.
Keunikan nilai-nilai Kampung Merdeka tergambar kuat dalam pelaksanaan prosesi pemakaman Y.T Ponganan, B.A., seorang bangsawan berusia 79 tahun dari wilayah Bongga Karadeng, yang wafat dan dimakamkan pada Rabu, 9 Juli 2025. Mendiang dikenal sebagai tokoh terhormat dan berpengaruh, namun pemakamannya berlangsung jauh dari kemewahan atau simbol status sosial seperti lazimnya pemakaman bangsawan di Tana Toraja.
Tidak ada kerbau belasan, tidak ada panggung megah, tidak ada atribut kebangsawanan yang mencolok. Semua prosesi berjalan dalam bingkai adat lokal Kampung Merdeka yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan antar warga.
“Di Kampung Merdeka ini semua sama. Semua tunduk pada adat yang berlaku, tanpa pandang status sosial. Inilah yang membedakan pelaksanaan Rambu Solo’ di sini dibanding tempat lain,” ujar Brigjen Pol Frans Barung Mangera, tokoh masyarakat yang turut hadir dalam upacara tersebut.
Kampung Merdeka menawarkan perspektif lain dalam melihat warisan budaya Toraja. Di tengah arus modernitas dan simbol-simbol status yang sering mendominasi pelaksanaan adat, masyarakat Pangorean justru menghadirkan kebijaksanaan lokal yang menempatkan semua orang sejajar di hadapan kematian dan adat.
Kisah ini menjadi pengingat bahwa makna sejati adat bukan terletak pada gemerlapnya prosesi, tetapi pada nilai-nilai yang dihidupi bersama—tentang solidaritas, kesederhanaan, dan penghormatan yang tulus kepada mereka yang telah berpulang.
Rambu Solo’ dan Kontras Kesederhanaan Kampung Merdeka
Secara umum, Rambu Solo’ adalah rangkaian upacara kematian adat Toraja yang berlangsung dengan penuh kemeriahan dan nuansa sakral. Tradisi ini biasanya digelar selama beberapa hari, bahkan hingga berminggu-minggu, melibatkan ratusan tamu undangan serta hewan kurban seperti kerbau dan babi.
Mayat biasanya diletakkan di tengah lapangan yang disebut lakkian, dihiasi dengan ornamen khas Toraja, dan dikelilingi oleh rumah-rumah adat sementara (tongkonan mini) sebagai tempat berkumpulnya pelayat serta keluarga besar.
Tidak hanya itu, peti jenazah pun kerap dibuat dengan ukiran khas Toraja yang rumit, bahkan dibubuhi ornamen emas atau perak sebagai simbol status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang semasa hidup, semakin mewah pula tata cara pemakamannya. Semua elemen ini diyakini akan memperlancar perjalanan roh menuju alam baka, yang dalam kepercayaan Toraja disebut Puya.
Namun, semua kemegahan itu tidak berlaku di Kampung Merdeka, Dusun Pangorean, Lembang Gasing. Di sini, tradisi Rambu Solo’ dijalankan dengan cara yang berbeda—lebih sederhana, egaliter, dan penuh penghormatan terhadap nilai kesetaraan.
Tak ada kerbau dalam jumlah besar, tak ada dekorasi mewah, dan tak ada penekanan pada status sosial dalam ritual. Semua orang dipandang sama di hadapan adat dan kematian, tanpa memandang gelar, keturunan, atau kekayaan.
Kampung Merdeka bukan menolak adat, tetapi menyaringnya dengan bijak, mengembalikan esensi Rambu Solo’ sebagai penghormatan yang tulus kepada orang yang telah meninggal, tanpa harus terjebak dalam simbolisme berlebihan.
Rambu Solo’ di Pangorean: Antara Kesederhanaan dan Kehormatan
Di Dusun Pangorean, Lembang Gasing, nilai kesetaraan bukan hanya semboyan, melainkan prinsip hidup yang dipegang teguh oleh seluruh warganya—bahkan hingga ke prosesi kematian. Dalam pelaksanaan Rambu Solo’, tidak ditemukan lakkian yang megah, tidak ada iringan ratusan kerbau, atau peti jenazah berhias emas mencolok seperti umumnya dalam adat Toraja.
Di sini, jenazah tidak diletakkan di tengah lapangan terbuka, melainkan cukup di halaman rumah duka, dengan suasana yang tenang dan penuh penghormatan. Semua prosesi dilakukan dengan sederhana, namun tetap bermakna.
“Petinya hanya diukir dengan pola-pola bermakna doa, tanpa riasan emas yang berlebihan. Bahannya pun dari kayu biasa,” jelas Brigjen Pol Frans Barung Mangera, tokoh masyarakat setempat.
Namun, kesederhanaan bukan berarti menghapus penghargaan terhadap status dan jasa almarhum. Dalam kasus Y.T Ponganan, B.A., bangsawan yang wafat pada Juli 2025, bentuk penghormatan tetap hadir—bukan lewat kemegahan, tetapi melalui simbol-simbol halus yang sarat makna. Di dalam petinya, disematkan sepasang keris emas dan bulan emas, lambang kehormatan dan kemakmuran yang hanya digunakan oleh kalangan tertentu.
Selain itu, proses pembuatan peti dan miniatur tongkonan dilakukan dengan penuh ketelitian, memakan waktu hampir satu bulan. Termasuk pula tau-tau, yaitu patung kayu yang menyerupai wajah almarhum, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan simbol bahwa sang jiwa telah menempuh perjalanan menuju Puya—alam baka dalam kepercayaan Toraja.
Dengan menyelaraskan nilai adat dan semangat kesederhanaan, Kampung Merdeka di Pangorean menghadirkan wajah lain dari Rambu Solo’—yang tidak kehilangan kehormatan, tapi juga tidak terjebak pada simbolisme berlebihan. Sebuah refleksi mendalam tentang kematian, warisan budaya, dan makna kemanusiaan.
Kampung Merdeka: Di Mana Adat adalah Harga Mati

Brigjen Pol Frans Barung Mangera, tokoh masyarakat dan saksi hidup tradisi lokal, menegaskan bahwa adat di Kampung Merdeka bukan sekadar aturan, tetapi prinsip hidup yang tak bisa ditawar. Ia mengisahkan bahwa pernah terjadi peristiwa kelam di masa lalu ketika seseorang mencoba mengabaikan ketentuan adat yang berlaku di dusun itu.
“Sudah ada yang terjadi. Itu menjadi pelajaran besar bagi kita semua agar tidak coba-coba melanggarnya. Di sini, aturan adat adalah harga mati,” ujarnya dengan nada serius dan penuh penghormatan.
Tak hanya dalam prosesi kematian, nilai-nilai kesetaraan yang dijunjung di Kampung Merdeka juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam sejarah lisan yang diwariskan turun-temurun, diceritakan bahwa pada masa lalu, setiap penunggang kuda—baik bangsawan maupun rakyat biasa—wajib turun dari pelana dan berjalan kaki ketika melintasi kawasan ini.
Aturan itu bukan tanpa makna. Ia menjadi simbol kerendahan hati dan penghormatan terhadap tanah adat, sekaligus penegasan bahwa di Kampung Merdeka, tidak ada satu pun manusia yang lebih tinggi dari yang lain di hadapan adat dan nilai-nilai bersama.
Keunikan inilah yang membuat Kampung Merdeka bukan hanya berbeda, tetapi juga menjadi cermin bagaimana tradisi bisa menjadi kekuatan pemersatu dan penjaga identitas, bahkan di tengah dunia yang terus berubah.
Penghormatan Sejati dalam Kesederhanaan

Bagi keluarga mendiang Y.T Ponganan, B.A., kesederhanaan dalam prosesi pemakaman bukan berarti mengurangi makna penghormatan. Andi Palloan, putra almarhum, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian upacara dilakukan dalam suasana khidmat dan penuh ketulusan.
“Semua proses dijalankan secara gotong royong dan sederhana. Tapi bagi kami, inilah bentuk penghormatan sejati yang jauh lebih berkesan daripada sekadar simbol-simbol kemewahan,” ungkapnya dengan nada haru.
Tak ada prosesi yang dipaksakan untuk terlihat mewah. Setiap elemen pemakaman dilandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, adat, dan cinta kepada orang tua—menghadirkan kehangatan yang lebih dalam dibanding kemegahan luar. Di Kampung Merdeka, kemuliaan terakhir seseorang tidak diukur dari jumlah kerbau atau ukiran peti, melainkan dari ketulusan orang-orang yang mengantarnya pulang.